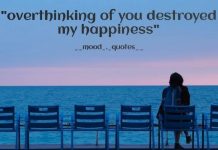SEORANG warga Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku bernama Henderjeta Ilelapotoa (40) terbaring sakit akibat kanker payudara yang dideritanya. Ia dan keluarganya tidak dapat menjalani perawatan di rumah sakit karena tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tidak memiliki biaya. Selama ini dia hanya menggunakan obat-obatan herbal. Kondisinya saat ini semakin parah, tidur hanya bisa menyamping dan tubuhnya juga sudah dipenuhi luka (Kompas, 27 Februari 2021).
Lain halnya dengan kisah Hamis Dalimotong, penduduk Pulau Lirang, Maluku Barat. Ia terpaksa dibawa naik boat ke Pulau Artauro, Timor Leste, beserta istri dan anaknya akibat borot di anus yang tak kunjung sembuh. Ternyata di Pulau Artauro, Hamis tidak bisa ditangani. Pemerintah Timor Leste lantas mengirim helikopter khusus untuk menjemput Hamis ke Dili. Setelah berbulan-bulan di Dili akhirnya Hamis meninggal akibat kanker anus stadium lanjut itu. Biaya perawatan Hamis dan keluarga untuk hidup berbulan-bulan di Dili sepenuhnya ditanggung pemerintah Timor Leste, tanpa harus menunjukkan KIS (Kompas, 2 April 2016).
Kasus Henderjeta dan Hamis hanyalah contoh kecil dari banyak kasus serupa di Indonesia. Tidak hanya dialami masyarakat di daerah terpencil, kondisi serupa juga terjadi di masyarakat di kota besar. Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang merata di Indonesia, mengharuskan pasien-pasien dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan tatalaksana medis lebih lanjut.
Rujukan ini memiliki konsekuensi yang tidak mudah bagi pasien dan keluarganya. Benar untuk biaya pengobatan saat ini ditanggung oleh pemerintah melalui KIS dan diharapkan semua biaya gratis untuk berobat. Namun bagaimana dengan biaya yang harus ditanggung pasien dan keluarganya untuk transportasi dan akomodasi selama menjalani perawatan di kota rujukan? Siapa yang harus menunggu para pasien? Bagaimana dengan keluarga atau anak-anak pasien yang mereka tinggalkan? Bagaimana dengan keluarga pasien yang harus meninggalkan pekerjaannya untuk menunggu pasien?
Masih merupakan jalan panjang bagi negara hadir sepenuhnya untuk menjaga kesehatan rakyatnya secara holistik.
Memahami Layanan Medik
Di pengujung jabatannnya, Dirut BPJS Kesehatan menyampaikan berita yang luar biasa menggembirakan. BPJS Kesehatan melaporkan arus kas positif Rp 18,7 triliun. Angka kepuasan peserta pada 2020 naik mencapai 81,5% dari tahun sebelumnya 80,1%. Sedangkan kepuasaan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 8,3% dari sebelumnya 79,1%. Pertanyaannya, apakah kepuasan pasien dapat dijadikan tolok ukur, bahwa layanan medik yang kita lakukan sudah benar dan berkualitas? Apakah surplus arus kas BPJS Kesehatan menjadi indikator bahwa layanan kesehatan kita sudah berada di jalur yang benar?
Perlu kita pahami bersama, bahwa sebutan “sudah dilakukan tindakan” dan “telah dilakukan tindakan dengan benar” adalah dua hal yang sangat berbeda.
Shortell, profesor bidang kebijakan kesehatan di California, Amerika Serikat, menyatakan layanan medik berbeda dengan layanan jasa lain karena memiliki banyak keunikan. Pertama, kebutuhan akan layanan medik selalu bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi. Kedua, proses layanan medik teramat kompleks, melibatkan kerja multidisiplin, dan butuh keahlian spesifik. Ketiga, mengukur luaran layanan medik itu tidak mudah. Keempat, toleransi terhadap kesalahan sangat amat kecil, mendekati nol. Kelima perbedaan kualitas pada layanan kesehatan tidak diperbolehkan, bahkan melanggar etika dan hukum. Keenam, keputusan tindakan medik tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan biaya. Semisal uang untuk membeli obat tidak cukup, maka kita tidak boleh mengambil obat hanya separuhnya saja. Apalagi untuk kasus-kasus yang mengancam nyawa.
Mengukur Kualitas
Mengukur kualitas layanan medik bukanlah pekerjaan mudah. Donabedian model sering dipakai sebagai pegangan oleh auditor profesional dalam mengukur kualitas layanan medik. Pengukuran ditujukan pada tiga unsur: struktur, proses, dan luaran mengikuti metodologi tertentu dan didasari kaidah ilmiah terkini. Jadi penilaian terhadap kualitas layanan medik hanya bisa dilakukan oleh auditor profesional yang berpengalaman.
Lantas apakah kepuasan pasien dapat menjadi tolok ukur kualitas layanan kesehatan? Barbara Starfield menyatakan, kepuasan pasien adalah indikator yang salah dalam mengukur kualitas layanan medik. Nancy O. Graham menjelaskan, pada layanan medik dikenal dua jenis penilaian. Pertama, penilaian produk medik, product quality, ini tentang what do you get (apa yang Anda dapatkan). Kedua, penilaian cara melayani, services quality, ini tentang how do you get (bagaimana Anda mendapatkannya). Kemampuan pasien untuk menilai amat terbatas, hanya sampai pada apa yang dirasakan saat dia dilayani, yaitu services quality, bukan product quality.
Contohnya apakah product quality pada penanganan kasus penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, dan stroke di daerah Ambon dan Papua sama dengan yang ada di Jakarta? Lantas, apakah kepuasan rakyat di daerah bisa menjadi ukuran product quality di daerah tersebut? Barbara Starfield menegaskan, pasien puas, belum tentu telah menerima pengobatan yang benar. Sebaliknya, pasien yang tidak puas, belum tentu telah menerima pengobatan yang tidak benar. Upaya meningkatkan indeks kepuasaan perlu diimbangi kepastian product quality. Apabila pengukuran tidak tepat, akan menuntun kita ke arah yang salah, dan semakin jauh dari tujuan kita untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Laporan Global Competitiveness Index World Economic Forum 2018-2019 menunjukkan, bahwa peringkat daya saing Indonesia ada di peringkat 50 (2019) turun 5 tingkat ke peringkat 45 (2018). Pilar kesehatan berada di peringkat 96 dari 141 negara. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Data di atas menunjukkan, bahwa sebelum pandemi Covid-19 negara kita sudah memiliki problematika serius mengenai kesehatan.
Sektor kesehatan tidak bisa dimasukkan dalam komoditas dagang karena dalam pelayanan medik tidak boleh ada perbedaan kualitas. Kualitas layanan medik harus dipastikan terlebih dahulu, baru kita menentukan berapa biayanya. Harga layanan harus sesuai standar kualitas karena ini masalah nyawa. Bukan sebaliknya seperti konsep asuransi KIS yang sedang kita jalani saat ini, harga dipatok kemudian kualitas ditentukan menyusul dengan menyesuaikan kondisi keuangan. Pelayanan publik terbaik adalah ketika negara dan aparatnya berhasil menyelamatkan nyawa. Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk menjadikan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Apabila itu diterjemahkan ke dalam tindakan yang benar, diharapkan tidak akan ada lagi kasus Henderjeta dan Hamis lain ke depannya.[]
* Residen Jantung dan Pembuluh Darah FKKMK UGM-RSUP Dr Sardjito dan Koordinator Tim Bantuan Residen Tim Mitigasi Dokter PB IDI